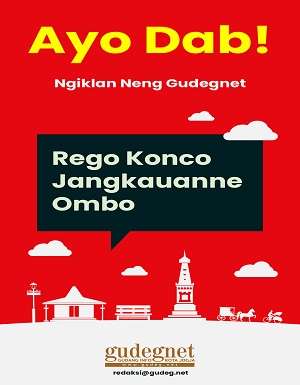Upacara Adat & Festival Budaya
Upacara Labuhan Parangkusumo dan Gunung Merapi Yogya
Kinahrejo, Umbulharjo, cangkringan, Sleman, Yogyakarta.

Ulasan
Upacara Labuhan Parangkusumo, Gunung Merapi Yogya dan Gunung Lawu
Jogja, Indonesia - www.gudeg.net Kraton Yogyakarta melaksanakan upacara Labuhan setiap tahunnya. Kata “labuh” artinya mirip kata “larung” yang bermakna membuang sesuatu ke dalam air baik sungai atau laut.
Secara sederhana upacara ini sendiri bisa diartikan sebagai aktivitas memberi sesaji / persembahan kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Tujuannya untuk keselamatan pribadi Sri Sultan, kraton serta rakyat Yogyakarta.
Sedangkan cara pemberian sesaji tergantung dari lokasi upacara Labuhan itu sendiri. Semisal, upacara Labuhan di Pantai Parangkusumo. Di pantai itu, pelaksanaan upacara labuhan dilakukan dengan cara melemparkan sesaji ke laut.
Berbeda halnya saat upacara ini dilaksanakan di gunung Merapi. Benda-benda sesaji hanya diletakkan di lereng gunung di sisi tengah atau dalam bahasa Jawa-nya disebut Kendit. Di gunung Lawu, upacara ini dilakukan di desa Dlepih. Caranya dengan meletakkan semua sesaji di atas “sela gilang” atau meja yang terbuat dari batu.
Awalnya, kerabat Kraton Yogyakarta yang melakukan upacara Labuhan ini, sehari setelah Pangeran Mangkubumi dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Lalu, seiring berjalannya waktu, upacara ini dilakukan terus menerus setiap tahun memperingati upacara penobatan seorang Sultan.
Tempat dilaksanakannya pun hanya ada tiga yaitu di pantai Parangkusumo, gunung Merapi serta gunung Lawu. Namun, sedikit berbeda saat menginjak perayaan sewindu ( delapan tahun berdasarkan penanggalan Jawa). Selain ketiga tempat tersebut, ditambah satu lokasi lagi di desa Dlepih, kecamatan Tirtomoyo, kabupaten Wonogiri.
Alasan pemilihan keempat tempat itu karena pertimbangan historis. Dulunya, raja-raja Mataram, terutama Panembahan Senopati bertapa dan terkoneksi dengan “roh halus” di sana. Lalu, muncul kepercayaan setiap raja yang berkuasa berkewajiban merawat relasi tersebut lewat sesaji. Anggapan yang berkembang “roh-roh” tersebut berperan dalam pendirian kerajaan Mataram, semisal Ratu Kidul yang berkuasa di laut selatan atau Nyai Widononggo di Dlepih, Wonongiri dan sebagainya.
Namun, saat Sri Sultan Hamengkubuwono IX berkuasa terjadi perubahan. Jika sebelumnya dilakukan satu hari sesudah ulang tahun penobatan, maka diubah satu hari setelah hari ulang tahun beliau menurut penanggalan Jawa yaitu 25 Bakdo Mulud. Alasan pergeseran itu karena beliau tidak mau memperingati hari penobatannya sebagai raja yang saat itu dilakukan imperialis Belanda.
Persiapan upacara Labuhan
Persiapan upacara Labuhan dilakukan tiga hari sebelum tanggal pelaksanaan. Sedangkan rangkaian upacara itu sendiri terdiri atas empat tahap yaitu : pembuatan jladren (adonan) kue apam, pembuatan apam, upacara peringatan ulang tahun Sri Sultan HB di kraton Yogyakarta, serta upacara Labuhan.
Para puteri keraton membuat adonan kue apam itu. Prosesi ini disebut ngebluk. Apamnya terdiri atas dua jenis yaitu apam biasa dan apam Mustoko. Apam biasa dibuat sebanyak 240 buah lalu ditata di atas wadah bernama Nyiru. Sedangkan, apam Mustoko dicetak sebanyak 40 buah.
Apam Mustoko unik. Apam ini memiliki garis tengah sepanjang 20 cm atau satu jengkal tangan laki-laki dewasa. Tebalnya sekitar 5 cm. Akibat ukuran yang panjang dan besar ini, bagian dalamnya sering masih mentah. Lebih menarik lagi karena para puteri kraton pembuatnya harus sudah tua dan masih perawan.
Saat membuatnya, para puteri kraton ini mengenakan pakaian adat Jawa yang terdiri atas kain panjang dan kemben / kain penutup dada yang disebut “ubed.” Permaisuri Sri Sultan mengambil jladren pertama kali sebelum proses pembuatan apam ini dilanjutkan. Kondisi berbeda terjadi saat Sri Sultan HB IX dimana beliau tidak memiliki permaisuri. Tugas pengambilan jladren itu lalu dilimpahkan kepada kerabat kraton yang paling tua silsilahnya, diteruskan puteri-puteri yang lain,
Diluar pembuatan apam, Widya Budaya, bagian dari keraton yang bertanggung-jawab mengurus upacara dan menyimpan naskah-naskah kuno bertugas menyiapkan benda-benda Labuhan dan membagikan benda-benda itu menjadi tiga bagian pada tahun biasa dan empat bagian pada tahun Dal lalu diletakkan di Parang Kusumo, gunung Merapi, gunung Lawu, serta desa Dlepih di Wonogiri.
Peran Widya Budaya
Widya Budaya berperan mengumpulkan benda-benda, bunga sesaji dari pusaka keraton yang “disucikan” tiap Jumat dan Selasa Kliwon dengan cara dikuntugi (diberi menyan). Bunga-bunga yang sudah layu dikumpulkan di tempat tertentu sampai hari Labuhan tiba.
Para puteri kraton yang tertinggi derajatnya bertugas mengumpulkan bunga-bunga itu dan beberapa perlengkapan lainnya seperti potongan kuku dan rambut Sri Sultan. Setelah siap, puteri kraton tersebut lalu menyerahkan kepada keparak yang tertinggi pangkatnya atau disebut juga Lurah Keparak untuk diletakkan di bangsal Proboyekso, atau bangsal tempat menyimpan benda-benda pusaka.
Semua benda dan properti Labuhan termasuk apam diletakkan di atas “ancak” – wadah yang dibuat dari bagian dalam bambu, dianyam dan berfungsi sebagai baki – lalu ditutup mori dan di tiap ancak diberi nama.
Selain itu ada emas, perak serta tembaga sebesar lidi dan setinggi ukuran badan Sri Sultan. Ketiganya tidak dilabuh, namun dipotong menjadi bagian kecil-kecil, lalu dibagikan kepada para pangeran serta bupati.
Saat Prosesi Keraton
Widya Budaya siap menjalankan upacara saat tanggal 25 Bakda Mulud bertepatan dengan hari ulang tahun Sri Sultan HB IX pada pukul 10.00 WIB. Seluruh pangulu dan kerabat kraton juga sudah siap di Tratag Bangsal Kencana bagian timur.
Prosesi berlanjut. Sesudahnya, apam, benda-benda Labuhan serta tumpeng yang berjumlah sesuai usia Sri Sultan atau yang disebut juga “hajad dalem” atau yang bermakna hajad Sri Sultan ini dikeluarkan dari Bangsal Proboyekso ke bangsal Kencana.
Selanjutnya pangulu membacakan doa dan setelah selesai para abdi dalem membawa benda-benda Labuhan ke bangsal Sri Panganti. Benda-benda tadi dimasukkan ke dalam kotak kayu yang tertutup. Setelah diinapkan semalam, esoknya benda-benda itu dibawa ke lokasi labuhan.
Upacara Labuhan Parangkusumo
Semalam sebelum upacara labuhan di pantai Parangkusumo, biasanya ada beberapa anggota masyarakat yang menginap di sana. Mereka berdoa kepada batu yang dianggap keramat di pantai Parangkusumo. Batu ini dikelilingi tembok berbentuk segi empat. Mitos yang tersebar menyebutkan dulunya batu itu bekas tempat semadi para raja Mataram serta tempat pertemuan antara raja Mataram dengan Ratu Pantai Selatan.
Saat upacara Labuhan dilakukan
Saat hari pelaksanaan upacara, biasanya anggota masyarakat datang sambil membawa bunga tabur. Ada yang percaya bunga tabur itu berkhaziat menyembuhkan orang sakit dan bisa mengabulkan cita-cita.
Juru kunci Parangkusumo atau dikenal sebagai bapak Bekel Puraksolono mendoakan para peziarah tersebut sambil memutarkan bunga-bunga sebanyak tiga kali. Bunga-bunga yang dibawa lalu diletakkan di atas wadah yang disebut pedupaan. Lalu, pada pagi harinya, tanggal 26 Bakda Mulud pukul 08.00 WIB, benda-benda itu diletakkan di sebuah wadah berbentuk rumah dan terbuat dari bambu yang disebut Jati Ngarang.
Para pegawai Widya Budaya membawa semua benda-benda itu dari pantai Parangtritis ke pantai Parangkusumo. Saat tiba di kecamatan Kretek, para pegawai kraton menyerahkannya kepada camat Kretek. Lalu, dari kantor kecamatan, para abdi dalem membawanya sambil berjalan kaki lalu diseberangkan menggunakan rakit. Kira-kira 1 km sebelum tiba pantai Parangkusumo, persisnya di bekas pesanggrahan para peserta Konferensi Kolombo, benda-benda yang diletakkan di Jati Ngarang dikeluarkan lalu ditata sebelum dilabuh.
Para abdi dalem lalu memisahkannya menjadi tiga bagian. Pertama, diletakkan di sebuah usungan berbentuk segi empat berukuran 1 meter persegi. Kedua, barang-barang ditempatkan di dalam tiga buah baki yang ditutup kain merah. Ada empat orang yang mengusung baki-baki tersebut. Agar mudah tenggelam bakul tersebut dibebani batu. Ketiga, ada baki lain yang dibawa tiga orang berisi benda-benda yang ditanam, antara lain potongan kuku, potongan rambut, pakaian bekas, serta “songsong/payung.” Semuanya mirip Sri Sultan. Ada juga “layon” bunga – bunga sesaji pusaka kraton yang sudah layu dan kering.
Setelah selesai melakukan upacara penanaman, para abdi dalem membawa benda-benda tersebut ke pantai Parangkusumo untuk dilabuh. Sebelum melabuh, juru kunci mengucapkan kalimat atau doa-doa pengantar labuhan.
Sesudah mengucapkan kalimat pengantar, juru kunci dan abdi dalem lalu melabuh benda-benda tersebut ke tengah laut. Begitu dilabuh, pengunjung menceburkan diri ke laut untuk berebut benda-benda tersebut. Sedangkan pada malam hari orang-orang datang mengambil benda yang ditanam di pantai Parangkusumo.
Pertanyaannya, kenapa benda-benda itu diperebutkan? Ada kepercayaan yang beredar bahwa benda-benda tersebut mempunyai kekuatan mistis dan bisa dijual kepada mereka yang membutuhkan.
Jenis Benda-Benda yang Dilabuh
Jenis benda yang dilabuh ada dua yaitu benda pokok dan benda pengiring. Benda-benda pokok itu ditujukan kepada Kanjeng Ratu Kidul. Sedangkan benda-benda pengiring kepada Nyai Rara Kidul, patih luar dari Ratu Kidul dan Nyai Riyo Kidul, patih dalam Ratu Kidul.
Benda-benda pokok yang dilabuh antara lain:
- Sinjang (kain panjang) Limar
- Sinjang Cangkring
- Sumekan ( kain penutup dada)
- Sumekan solok
- Sumekan gadhung mlathi
- Sumekan gadhung
- Sumekan udaraga
- Sumekan jingga
- Sumekan bangun Tulak
- “Wangkidan” kuluk kaniraga
- Wangkidan pethak / putih
- Songsong gilap
- Gelaran pasir kesasaban mori
- “Selo” (kemenyan) dan konyoh (param)
- “Arta” (uang) tindih Rp. 8,33
Benda-benda pengiring yang dilabuh berupa:
- Sinjang poleng
- Sinjang tulung watu
- Sumekan dringin
- Sumekan songer
- Sumekan pandhan binethot
- Sumekan solok
- Sumekan podhang ngisep sari
- Sumekan gadhung mlathi
- Sumekan bangun tulak
- Kemenyan, ratus dan param
- Pethi sapetadhahan
- “Lorodan agem dalem” barang bekas kepunyaan Sri Sultan
- Lanyon sekar
Labuhan di Gunung Merapi
Setelah selesai upacara Labuhan di pantai Parangkusumo, upacara labuhan berikutnya di gunung Merapi. Prosesinya para abdi dalem menyerahkan benda-benda Labuhan kepada bupati Sleman dan stafnya lalu diteruskan kepada juru kunci gunung Merapi di Cangkringan.
Lokasi labuhan di gunung Merapi ini di bagian kendhit, lereng tengah gunung Merapi di sisi selatan. Para abdi dalem menempatkan benda-benda Labuhan di dalam peti. Sebelumnya, juru kunci mengambil peti lama yang digunakan upacara Labuhan sebelumnya yang sudah kosong, lalu diganti peti baru yang berisi benda-benda labuhan. Sesudahnya, juru kunci menyerahkan benda-benda itu kepada para danyang sambil diberi kalimat pengantar seperti halnya saat upacara labuhan di pantai Parangkusumo.
Adapun benda-benda labuhan yang dibawa antara lain:
- Sinjang limar
- Sinjang cangkring
- Sinjang bangun tulak
- Sinjang gadhung
- Destar (kain penutup kepala)
- Peningset (ikat pinggang) udaraga
- Peningset jingga
- Kambil watangan
- Kampung poleng
- Ses (rokok) wangen
- Sela (kemenyan), ratus dan koyoh
- Yatra (uang) tindih Rp. 8,33
Setelah selesai mendoakan barang-barang labuhan dalam bahasa Arab, maka selesailah upacara labuhan di gunung Merapi itu.
Labuhan di Gunung Lawu
Seperti halnya labuhan di panti Parangkusumo dan gunung Merapi, labuhan di gunung Lawu ini bertujuan untuk mendatangkan keselamatan bagi raja, kraton serta warga Yogyakarta.
Alurnya, setelah abdi dalem sampai di kabupaten Karanganyar, maka bersama-sama petugas setempat melanjutkan perjalanan ke kelurahan Tawangmangu. Mereka yang ikut labuhan antara lain petugas dari Kraton, staf pemerintahan dari Kabupaten Karanganyar, kelurahan Tawangmangu, juga juru kunci (sadhu) dari gunung Lawu.
Setelah diinapkan semalaman, maka keesokan paginya Abdi Dalem menyerahkan benda-benda Labuhan itu kepada juru kunci (sadhu) dari gunung Lawu. Juru kunci lalu membawanya ke Arga Dalem di gunung Lawu dengan berjalan kaki. Lalu, sesampainya di Arga Dalem diadakan selamatan sekali lagi. Benda-benda Labuhan itu diletakkan di atas meja dari batu atau disebut juga “Sela Gilang”.
Labuhan di gunung Lawu ditujukan kepada:
Sunan Lawu I
Sunan Lawu I merupakan putera raja Mojopahit terakhir yang dulu bernama Raden Gugur. Beliau disebut juga Kasepuhan.
Sunan Lawu II
Sunan Lawu II ialah putera Sunan Lawu I. Beliau ialah Kaneman.
Benda-benda Labuhan di gunung Lawu:
- Untuk Kasepuhan
- Sinjang Limar
- Kampuh Poleng
- Dhestar Daramulak
- Pengiring labuhan untuk Kasepuhan :
- Sinjang Cangkring
- Sumekan gadhung
- Sumekan dringin
- Sumekan songer
- Sumekan teluh watu
- Sumekan jamben
- Songsong pethak seret praos
- Pengiring Labuhan untuk Kaneman
- Sinjang Cangkring
- Sumekan gadhung
- Sumekan dringin
- Sumekan songer
- Sumekan teluh watu
- Lurik kepyur
- Songsong pethak seret praos
- Sela (kemenyan), ratus konyoh, param
- Arta / uang tindih Rp. 8,33
Setelah itu juru kunci mengucapkan kalimat pengantar dalam bahasa Jawa.
Sesaji di dalam kraton
Selain tempat-tempat yang telah ditunjuk, kerabat kraton juga melakukan ritual dan meletakkan sesaji di dalam kraton yang ditujukan kepada kyai Ageng Pleret, kyai Jegod serta kyai Joyudo.
Sesaji kepada kyai Ageng Pleret berupa kambing, ambeng yang berisi nasi rasulan, 2 ambeng berisi nasi golong, 2 ambeng nasi ruwahan, 1 ambeng dahar adem-ademan, 1 sisir pisang dan sirih serta makanan dan buah-buahan yang dibeli di pasar.
Sedangkan kepada Kyai Jegod, para abdi dalem menyiapkan sesaji berupa 1 botol jenewer dan 1 botol legen. Kyai Jegod merupakan roh halus, yang dipercaya menghuni bangsal Proboyekso di kraton Yogyakarta.
Untuk Kyai Joyudo, abdi dalem mempersembahkan sesaji berupa 1 tube candu, roti, beberapa batang rokok, kopi tanpa gula, gula kelapa, juadah, mata uang yang diputihkan dengan kapur serta 1 ekor ayam hidup. Kyai Joyudo merupakan roh halus yang dipercaya menjaga sungai Winanga yang mengalir di sebelah barat kota Yogyakarta.
Pada soko guru (tiang utama) di bangsal Kencono dan Proboyekso, para abdi dalem meletakkan tumpeng mustoko yang terdiri atas sebuah gunungan tumpeng, Lombok, brambang serta terasi serta tumpeng berwarna yang disebut tumpeng waran.